B. Torehan Kolonial
Negara Indonesia secara yuridis memang baru berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, jika berbicara demokrasi Indonesia mustinya dibicarakan sejak Indonesia merdeka tersebut. Akan tetapi dalam perspektif waktu, kehadiran Republik Indonesia sesungguhnya melalui proses yang panjang, terutama masa Kolonial. Jima demokrasi dipandang sebagai pagam yang anti otokrasi, maka sesungguhnya demokrasi memiliki akar juga di masa Kolonial. Untuk itu sebagai
kajian historis, perlu kiranya dilacak akar-akar demokrasi yang pernah diciptakan pada masa kolonial.
Negara Kolonial (Hindia Belanda) sesungguhnya bukan sebuah negara
demokrasi. Akan tetapi di negeri induknya dijalankan sistem pemerintahan demokrasi. Ide-ide demokrasi berpengaruh terhadap pemikiran para pejabat kolonial, sehingga banyak muncul pemikiran untuk mengubah tatanan pemerintahan yang dianggapnya sebagai “feudal”. Percobaan demokrasi di Indonesia pada masa Kolonial dimulai dari tingkat desa. Ini sangat menarik untuk dicermati karena banyak pengamat yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan sistem yang asli di Indonesia, terutama di tingkat desa.
Pertanyaannya mengapa ujicoba demokrasi dimulai dari desa?
Jan Breman (1979) mengemukakan bahwa paham yang mengatakan bahwa desa-desa di Jawa yang dikatakan sebagai desa demokratis sesungguhnya konstruksi kolonial. Desa-desa yang dikatakan “asli”, sebelum mendapat sentuhan Kolonial adalah kepanjangan tangan atau bagian dari sistem feudal yang lebih tinggi dalam tatanan masyarakat Jawa. Hal ini sesuai dengan temuan Wasino (2008) yang
membuktikan bahwa di wilayah pusat kekuasaan Jawa, Surakarta tidak ada pemilihan kepala desa hingga awal kemerdekaan. Desa-desa di wilayah tersebut merupakan desa-desa yang terlambat menerima pengaruh Kolonialisme.
Menurut Schiecke (1929) desa-desa di Jawa bukanlah sebuah rumah tangga tertutup yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Desa-desa itu sesungguhnya bagian dari struktur dualistik dari sistem kerajaan Jawa yang mendasarkan diri pada pembagian wilayah terdiri dari lingkungan keraton dan desa. Kepala desa merupakan penghubung antara petani dengan administrasi kerajaan. Situasi ini berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke -18. Kepala-kepala desa diangkat berdasarkan keturunan, dan yang masih dianggap setia kepada administrasi kerajaan. Sejak abad XIX, Pemerintah Kolonial Belanda secara`resmi berkuasa atas wilayah Jawa. Sejak itu ada pemikiran bagaimana menguasai pemerintahan hingga tingkat desa agar dapat digunakan sebagai pendukung kebijakan-kebijakan Kolonial.
Salah satu caranya adalah memangkas hubungan feodal masyarakat Jawa dengan cara memperkuat institusi desa. Daendels pada tahun 1809 mulai memperkenalkan sebuah sistem pemungutan suara pada tingkat paling bawah. Di Cirebon, yang termasuk dalam wilayah Priangan di desa-desa yang lebih besar diangkat dua orang kepala (
Kuwu atau mantri dan dan prenta atau pretinggi). Sementara itu pada desa-desa yang lebih kecil hanya diangkat seorang parenta atau lurah. Dukuh-dukuh yang kurang dari enam keluarga digabungkan ke desa terdekat dan penduduknya dipaksa pindah ke sana. Tradisi pemilihan kepala desa yang dibuat di Cirebon awal abad XIX
itu berkembang di kebanyakan desa-desa yang dikuasi secara langsung oleh Pemerintah Kolonial Belanda, misalnya di Pati di Jawa Tengah (Husken,1998).
Tradisi pemilihan kepala desa itu yang kini berlanjt dan dikenal sebagai demokrasi desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi yang menjadi ikon masyarakat desa pada saat ini asal-usulnya adalah sebuah konstruksi Kolonial.
Pada level nasional, awal mula berkembangnya gagasan dan konsep demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan situasi sosial politik masa kolonial pada tahun-tahun pertama abad ke-20 yang ditandai dengan beberapa perkembangan penting: Pertama, mulai terbuka terhadap arus informasi politik di tingkat global. Kedua, “migrasi” para para aktifis politik berhaluan radikal Belanda, umumnya mereka adalah para buangan politik, ke Hindia Belanda. Di wilayah yang baru ini mereka banyak memperkenalkan ide-ide dan gagasan politik modern kepada para pemuda bumiputera. Dapat dicatat disini para “migran politik’ tersebut antara lain; Bergsma, Baars, Sneevliet, dan beberapa yang lain. Ketiga, transformasi pendidikan di kalangan masyarakat pribumi (van Niel,1984).
Pemikiran tentang demokrasi mengelora di sejumlah aktivis pergerakan. Maka terbentuklah organisasi-organisasi yang berhaluan politik untuk menyuarakan suara rakyat di dalam sebuah sistem Kolonial. Suara-suara itu ada yang disalurkan melalui parlemen dan ada yang di di luar parlemen Hindia Belanda yang dikenal sebagai
Volksraad atau Dewan Rakyat. Banyak anggota partai politik yang tidak bersedia duduk dalam parlemen Hindia Belanda itu, seperti para aktivis PNI, ISDV, NIP, dan sebagainya. Mereka dikenal sebagai kaum nasionalis radikal. Akan tetapi banyak juga, yang dikenal sebagai kaum nasionalis moderat yang bersedia duduk di Parlemen untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dalam lembaga demokrasi
bentukan Belanda itu (Budi Utomo, 1995).
Saya kira perlu dikemukakan secara khusus tentang lembaga yang dinamakan Volsraad ini karena merupakan tempat berlatih demokrasi prosedural pasca Indonesia merdeka. Lemabaga ini d ibentuk sebagai dampak gerakan nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia I (1914-1918).
Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 (Ind. Stb. No. 114 Tahun 1917) dengan dilakukannya penambahan bab baru yaitu Bab X dalam Regeerings Reglement 1914 yang mengatur tentang pembentukan Volksraad. Pembentukan tersebut baru terlaksana pada tahun 1918 oleh Gubernur Jeneral Mr. Graaf van Limburg Stirum.
Volksraad sebagai sebuah lembaga dalam konteks Indonesia sebagai wilayah jajahan pada saat itu memang hanya merupakan basa basi politik pemerintahan kolonial.
Lewat pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit, komposisi keanggotaan Volksraad pada mulanya tidak begitu simpatik.
Pemilihan orang untuk mengisi jabatan Volksraad diawali dengan pembentukan berbagai “Dewan Kabupaten” dan “Haminte Kota”, di mana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih “Wali Pemilih” (Keesman). Kemudian Wali Pemilih inilah yang berhak memilih sebagian anggota Dewan Kabupaten. Kemudian setiap provinsi
mempunyai “Dewan Provinsi”, yang sebagian anggotanya dipilih oleh Dewan Kabupaten dan Haminte Kota di wilayah provinsi tersebut. Sebagian besar anggota Dewan Provinsi yang umumnya dari bangsa Belanda, diangkat oleh Gubenur Jenderal. Susunan dan komposisi Volksraad yang pertama (1918) beranggotakan 39 orang (termasuk ketua), dengan perimbangan:
1. Dari jumlah 39 anggota Volksraad, orang Indonesia Asli melalui “Wali Pemilih” dari “Dewan Provinsi” berjumlah 15 anggota (10 orang dipilih oleh “Wali Pemilih” dan 5 orang diangkat oleh Gubernur Jenderal)
2. Jumlah terbesar, atau 23 orang, anggota Volksraad mewakili golongan Eropa dan golongan Timur Asing, melalui pemilihan dan pengangkatan oleh Gubernur Jenderal (9 orang dipilih dan 14 orang diangkat).
3. Adapun orang yang menjabat sebagai ketua Volksraad bukan dipilih oleh dan dari anggota Volksraad sendiri, melainkan diangkat oleh mahkota Nederland (Marbun, 1992).
Kebanyakan anggota Volksraad berasal dari dewan-dewan Kota Praja dan keresidenan, dan sebagian lagi diangkat oleh gubernur jenderal. Ketika itu telah terpilih 10 dari 15 orang bumiputra yang dicalonkan. Sutherland menyebutkan bahwa ada empat orang bupati yang menjadi anggota dewan rakyat saat pembentukannya, yaitu: Koesoemo Oetojo, Djajadiningrat, Koesoemojoedo dan Soejono. Sutherland (1983:178).
Dalam perkembangannya, Volksraad mengalami peubahan jumlah anggota.
Pada tahu 1927, lembaga ini terdiri dari seorang ketua yang diangkat oleh raja Belanda dengan anggota 55 orang. Ketika itu anggota dari kalangan bumiputra hanya 25 orang. Pada tahun 1930, Volksraad terdiri dari 1 orang ketua, dan 60 orang anggota. Anggota Volksraad dari kalangan bumiputra sebanyak 30 orang.
Setelah banyak orang Indonesia yang berpengalaman dalam dewan rakyat, maka muncul beberapa usul anggota untuk mengubah susunan dan pengangkatan Volksraad ini agar dapat dijadikan tahap menuju Indonesia merdeka, namun selalu ditolak. Salah satunya adalah “Petisi Sutardjo” pada tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia. Petisi ini juga ditolak pemerintah kolonial Belanda.
C. Demokrasi Parlementer/ Liberal
Setelah Hindia Belanda berada di bawah pendudukan Jepang, lembaga Volksraad dibubarkan. Sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan militer, sehingga demokrasi sama sekali mengalami kemandegan. Kondisi ini baru mengalami perubahan berarti setelah Indonesia merdeka.
Momentum historis perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan di tandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Hatta. Dalam maklumat ini dinyatakan perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai
politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru. Pada tahun 1953 Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1953 Pemilu. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk pemilhan parlemen)
dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante).
Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di
Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.
Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini
diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen). Partaipartai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Partai Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD, ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso.
Pemilu pertama nasional di Indonesia ini dinilai berbagai kalangan sebagai proses politik yang mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan representativness.Fragmentasi politik yang kuat berdampak kepada ketidakefektifan kinerja parlemen hasil pemilu 1955 dan pemerintahan yang dibentuknya. Parlemen baru ini tidak mampu memberikan
terobosan bagi pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil, tetapi justru mengulangi kembali fenomena politik sebelumnya, yakni “gonta-ganti” pemerintahan dalam waktu yang relatif pendek.
Ketidakefektifan kinerja parlemen memperkencang serangan-serangan yang mendelegitimasi parlemen dan partai-partai politik pada umumnya. Banyak kritikan dan kecaman muncul, bahkan tidak hanya dilontarkan tokoh-tokoh “anti demokrasi”.
Hatta dan Syahrir menuduh para politisi dan pimpinan partai-partai politik sebagai orang yang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan keuntungan kelompoknya, bukan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun begitu, mereka tidak menjadikan demokrasi parlementer sebagai biang keladi kebobrokan dan kemandegan politik. Hal ini berbeda dengan Soekarno yang menempatkan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal sebagai sasaran tembak. Soekarno lebih mengkritik pada sistemnya.
Kebobrokan demokrasi liberal yang sedang diterapkan, dalam penilaian Soekarno, merupakan penyebab utama kekisruhan politik. Maka, yang paling mendesak untuk keluar dari krisis politik tersebut adalah “mengubur” demokrasi liberal yang dalam pandangannya tidak cocok untuk dipraktikkan di Indonesia. Akhirnya, Soekarno menyatakan demokrasi parlementer tidak dapat digunakan untuk revolusi, “parliamentary democracy is not good for revolution”.
Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960.
Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945
Bersambung ….
![clip_image001[4] clip_image001[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTsFTEw4t54Z0tNenXbk7KMJbO_koxmLABIPwYFxTnCGNnJiBwZ66i-0cORZ5j-99PqleP4OJcBMW7JghvU5fyACaj5f7Gl3or7dipF4kCHDoE1jjn8OI475Eq8oVzIm9KpO_Xd9qhwlQ/?imgmax=800)
![clip_image002[4] clip_image002[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8bpI8VoDPAUl4S36up9BG8Bv949BU7-GIz9KjbYIVMwprUHchCJI8NUdIygCbmh_5IUBwYXt8ZRzH9j5n7qln8dotMv5SkKgVG_LEYmOQyKBxH88lPkWJ8-M4q43YiYgbeEjwgAGJOy4/?imgmax=800)
![clip_image003[4] clip_image003[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv3ajIBSRVak9Pr62tbfkCGWZ84wEDQ80ms7qCldN5dmQjpP1yqFHhDpJpLVcjIct1dyHt1gKhLeGhizeeUG7-7JHa2qXv5bo_R-yTZl6YGsI1HM6LyyIMpWFdnPRbE4MivdV93XfzL5Y/?imgmax=800)
![clip_image004[4] clip_image004[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdY7E2eEihSL1NbY9He3E-KmQhyphenhyphenFSORyL8Ue6DuwySVXIiDozSlU5wzxsQ9JgCC6s7d_YyYunr6nLotuYqE02-QA2-vwWcWHX454Xta2_vmQGI_r7UZ1P4knkyOWjI7WSJ4a-j_-L6sew/?imgmax=800)
![clip_image005[4] clip_image005[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9uihdbezYshwVEZRIlcVQ0ryZP8ygmA3zxi6TuoyqCMu_Zo4KT6yCLDBy3oYyGTil-lygiwVGBtZBHxY8IARWVhBVe3wV_l2BwgM4DvIygU5IRtAGMzFVIa0Kggb7QZXF2gZX96BPJl4/?imgmax=800)
![clip_image007[4] clip_image007[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV-F0SEJj1cjOL_9_qWxCqyCOqQxuFZ7dDQbgqdUewN54dMUevFYPMMJCC21J_5lvGbH8S1bHQWwzNbwegm5r-IFRPW-OpJOlVqHjJSI5riAKx8nvtagVPgRfs9bUd3y8-xl8DCkYmzq0/?imgmax=800)
![clip_image008[4] clip_image008[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5iffYmbgbW3q4BNNkWWfXup82F4Zj_FRau-leAqRGaAE_gL6dj52XbbN6nhS1oa16tHXnISQFQ9tck3QHckCLQg8T8DD5M4qgp17MO3oIEwjbEdsfdRvw3IA4RuIwTXhB6BJNDbruvfw/?imgmax=800)
![clip_image009[6] clip_image009[6]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR-yuimt8pHpBacNKav-1H6HtcOVcNo2fNTdkSAB6roIo5_76dTqAwQv7gq4YQKCCNRlF2HsdIZsxbPmtXOYk4z9F6Tsz-M5FdZTgBdPZerdzQRBA35OY_Z6Ynme8yR8tPa0aJk6mdqU8/?imgmax=800)
![clip_image010[4] clip_image010[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX9wnNzngEafu_IEZ892ArievscS6ho1ea-idKCy8YzRlxzQnwYbWSTKVyPnYS6_O8lyyDPkVrjEzuTnx5sOLLEmeoLSYoyQxVD21PcLVMYZdjSZm2N8nhyScLZ0iEqzC9uo3rwJsP7v0/?imgmax=800)
![clip_image009[7] clip_image009[7]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6J-9W4GKwrkbXi4oFt0_wuVB7_81fhAHc0faFp738mmY5oFpQKR8gwxS5Kdp0hxvcqHBrgB_BJWAG-jzg-eBCbEsUw107vSElZIowD5zsLlcl0JRH_L1COaPScd9PT4t5H6vdRAHBsqo/?imgmax=800)
![clip_image011[4] clip_image011[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv17gT2BHe6b3BZhWwU6k4PziPk8ddEFm8sYTO2W5VC5ONSn-hzmxFL6SZL8ibY8xzz42-blWvawFbcZSoS7ubRQWlAB0qSkHhhXyAqNStY4kZqDz1AiG0Y4ZIkFfmWhalnFhoHqxFEKs/?imgmax=800)












 Tak lama kemudian, ia pun menyatakan akan membuka hubungan dagang dengan Israel, negara yang dibenci banyak orang di Indonesia. Pernyataan ini mengundang reaksi keras dari beberapa komponen Islam.
Tak lama kemudian, ia pun menyatakan akan membuka hubungan dagang dengan Israel, negara yang dibenci banyak orang di Indonesia. Pernyataan ini mengundang reaksi keras dari beberapa komponen Islam.  Namun seperti kata pepatah: Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Di mata banyak orang, kepercayaan diri Gus Dur tampak terlalu berlebihan. Ia sering kali melontarkan pendapat dan mengambil kebijakan yang kontroversial. Penglihatannya yang semakin buruk mungkin juga dimanfaatkan oleh para pembisik di sekitarnya. Gus Dur pun sering kali mengganti anggota kabinetnya dengan semaunya berpayung hak prerogatif. Tindakan penggantian menteri ini berpuncak pada penggantian Laksamana Sukardi (PDIP-pemenang Pemilu 1999) dari Jabatan Meneg BUMN dan Jusuf Kalla (Golkar-pemenang kedua Pemilu 1999) dari jabatan Menperindag, tanpa sepengetahuan Wapres Megawati dan Ketua DPR Akbar Tandjung.
Namun seperti kata pepatah: Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Di mata banyak orang, kepercayaan diri Gus Dur tampak terlalu berlebihan. Ia sering kali melontarkan pendapat dan mengambil kebijakan yang kontroversial. Penglihatannya yang semakin buruk mungkin juga dimanfaatkan oleh para pembisik di sekitarnya. Gus Dur pun sering kali mengganti anggota kabinetnya dengan semaunya berpayung hak prerogatif. Tindakan penggantian menteri ini berpuncak pada penggantian Laksamana Sukardi (PDIP-pemenang Pemilu 1999) dari Jabatan Meneg BUMN dan Jusuf Kalla (Golkar-pemenang kedua Pemilu 1999) dari jabatan Menperindag, tanpa sepengetahuan Wapres Megawati dan Ketua DPR Akbar Tandjung.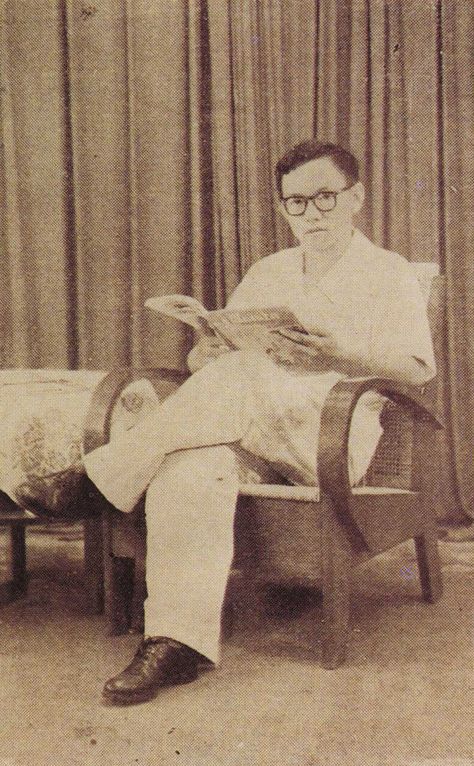 Lalu terkuaklah kasus Buloggate dan Bruneigate. Gus Dur diduga terlibat. Kasus ini membuahkan memorandum DPR. Setelah Memorandum II tak digubris Gus Dur, akhirnya DPR meminta MPR agar menggelar Sidang Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
Lalu terkuaklah kasus Buloggate dan Bruneigate. Gus Dur diduga terlibat. Kasus ini membuahkan memorandum DPR. Setelah Memorandum II tak digubris Gus Dur, akhirnya DPR meminta MPR agar menggelar Sidang Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Gus Dur pun tergolong rajin melontarkan kritik kepada pemerintah. Kritikan itu lama-lama menyebabkan Pak Harto risih. Puncaknya terjadi pada Mukhtamar NU di Cipasung 1994. Pemerintah berupaya menjegal Gus Dur. Tapi Gus Dur tetap terpilih untuk periode kedua. Hal ini terekspresikan dari ketidaksudian Presiden Soeharto menerima Gus Dur dan pengurus PBNU lainnya.
Gus Dur pun tergolong rajin melontarkan kritik kepada pemerintah. Kritikan itu lama-lama menyebabkan Pak Harto risih. Puncaknya terjadi pada Mukhtamar NU di Cipasung 1994. Pemerintah berupaya menjegal Gus Dur. Tapi Gus Dur tetap terpilih untuk periode kedua. Hal ini terekspresikan dari ketidaksudian Presiden Soeharto menerima Gus Dur dan pengurus PBNU lainnya. Selain menjadi idola bagi banyak orang, Gus Dur juga menjadi idola bagi keempat puterinya: Alisa Qortrunnada Munawarah (Lisa), Zannuba Arifah (Venny), Anisa Hayatunufus (Nufus) dan Inayah Wulandari (Ina). Hal ini tercermin dari pengakuan puteri sulungnya Lisa. Lisa bilang, sosok tokoh LSM Gus Dur menurun padanya, bakat kolumnis menurun ke Venny, kesastrawanannya pada Nufus dan sifat egaliternya pada Ina.
Selain menjadi idola bagi banyak orang, Gus Dur juga menjadi idola bagi keempat puterinya: Alisa Qortrunnada Munawarah (Lisa), Zannuba Arifah (Venny), Anisa Hayatunufus (Nufus) dan Inayah Wulandari (Ina). Hal ini tercermin dari pengakuan puteri sulungnya Lisa. Lisa bilang, sosok tokoh LSM Gus Dur menurun padanya, bakat kolumnis menurun ke Venny, kesastrawanannya pada Nufus dan sifat egaliternya pada Ina.